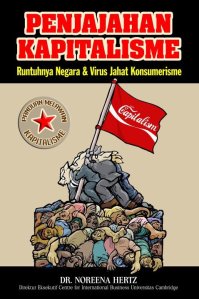PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS
Paulo Freire
Rasa “takut kebebasan” yang menimpa kaum tertindas,(rasa takut kebebasan ini juga dapat ditemukan dalam diri para penindas, sekalipun, dalam bentuk yang berbeda. Kaum tertindas takut untuk merangkul kebebasan: sementara kaum penindas takut kehilangan “kebebasan” untuk menindas) ketakutan yang baik mendorong mereka untuk menginginkan peranan sebagai penindas maupun mengurung mereka tetap sebagai orang tertindas, harus ditelaah.
Pendidikan kaum tertindas ini, yang dijiwai oleh kedermawanan sejati, kemurahan hati humanis (bukan humanitarian) menampilkan diri sebagai sebuah pendidikan bagi seluruh umat manusia. Pendidikan yang dimulai dengan kepentingan egoistis kaum penindas (egoism dengan baju kedermawanan palsu dari paternalism) dan menjadikan kaum tertindas sebagai obyek dari humanitarianisme mereka, justru mempertahankan dan menjelmakan penindasan itu sendiri. Dia merupakan sebuah perangkat dehumanisasi. Itu pula sebabnya mengapa, sebagaimana telah kita tegaskan sejak awal, pendidikan kaum tertindas tidak dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh kaum penindas.
Pendidikan kaum tertindas, sebagai pendidikan para humanis dan pembebas, terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, kaum tertindas membuka tabir dunia penindasan dan melalui praksis melibatkan diri untuk mengadakan perubahan. Pada tahap kedua, di mana realitas penindasan itu sudah berubah, pendidikan ini tidak lagi menjadi milik kaum tertindas tetapi menjadi pendidikan untuk seluruh manusia dalam proses mencapai kebebasan yang langgeng.
Dalam kedua tahap ini dibutuhkan gerakan yang mendasar agar kultur dominasi dapat dilawan secara kultural pula. Pada tahap pertama, maka perlawanan itu terjadi dalam hal kaum tertindas menyadari akan adanya dunia penindasan; dan pada tahap kedua, dengan memberantas habis mitos – mitos yang diciptakan dan dikembangkan di masa orde lama, yang bagaikan hantu – hantu yang menghantui bangunan baru yang muncul dari perubahan revolusioner.
Pada tahapnya yang pertama pendidikan ini harus membahas masalah kesadaran kaum tertindas dan kaum penindas, yakni masalah manusia yang menindas dan manusia yang menderita penindasan itu. Bahasan itu harus mencakup masalah perilaku, pandangan dunia serta etika mereka. Suatu masalah khas dalam hal ini adalah dualitas kaum tertindas: mereka adalah manusia kontradiktif dan terbelah, dibentuk dan hidup dalam situasi penindasan dan kekejaman yang nyata.
Kesadaran kaum penindas cenderung untuk mengubah segala sesuatu disekitarnya menjadi obyek kekuasaan mereka. Bumi, harta kekayaan, produksi, karya cipta manusia, manusia itu sendiri, waktu – semuanya direduksi menjadi obyek yang berada di bawah kemauannya.
Dalam semangat mereka untuk memiliki secara tak terbatas, kaum penindas mengembangkan semacam keyakinan bahwa adalah mungkin bagi mereka mengubah segala sesuatu menjadi obyek daya beli mereka; di sinilah dasar dari konsep kehidupan materialistic mereka yang kokoh. Uang menjadi ukuran segalanya, dan laba adalah tujuan paling utama. Bagi kaum penindas, apa yang dianggap bermanfaat adalah memiliki lebih banyak – selalu lebih banyak – sekalipun dengan mengorbankan kaum tertindas yang semakin miskin dan tidak memiliki apa – apa lagi. Bagi mereka, mengada adalah memiliki dan mengada sebagai kelas masyarakat “berpunya”.
Kaum penindas tidak menyadari monopoli mereka untuk memilih lebih banyak sebagai suatu hak istimewa justru menjadikan orang lain dan diri mereka sendiri tidak manusiawi. Mereka tidak mengerti bahwa dalam melampiaskan sikap mementingkan diri sendiri untuk memiliki sebagai sebuah kelas penguasa, mereka tercekik oleh milik mereka sendiri dan bahwa mereka tidak mengada; mereka hanya memilki.
Penindas dan tertindas ternyata masuk dalam lingkar pendidikan. Dalam pendidikan ini (sekolah) terdapat sebuah fenomena yang cukup unik fenomena ini disebut Fatalism. Fatalism ini sering kali ditafsirkan sebagai suatu kepatuhan yang menjadi ciri kepribadian nasional. Fatalism dalam samarannya berupa sikap serba patuh adalah suatu hasil dari suatu situasi kesejarahan dan kemasyarakatan. Inilah yang terjadi pada kasus hubungan antara guru – murud di institusi pendidikan.
Suatu analisis yang cermat tentang hubungan antara guru – murid pada semua tingkatan, baik dalam maupun luar sekolah, mengungkapkan watak bercerita (narrative) yang mendasar di dalamnya. Hubungan ini melibatkan seorang subyek yang bercerita (guru) dan obyek – obyek yang patuh dan mendengarkan (murid – murid). Isi pelajaran yang diceritakan, baik yang menyangkut nilai – nilai maupun segi – segi empiris dari realitas, dalam proses cerita cenderung menjadi kaku dan tidak hidup. Pendidikan menderita penyakit cerita semacam itu. (bukan pengalaman murid)
Ciri yang sangat menonjol dari pendidikan bercerita ini, karena itu, adalah kemerduaan kata – kata, bukan kekuatan pengubahnya. “Empat kali empat sama dengan enam belas, ibu kota Para adalah Belem”. Murid – murid mencatat, menghafal dan mengulangi ungkapan – ungkapan tersebut tanpa memahami apa arti sesungguhnya dari empat kali empat, atau tanpa menyadari makna sesungguhnya dari kata “ibu kota” dalam ungkapan “ibu kota Para adalah Belem”, yakni apa arti Belem bagi Para dan apa arti Para bagi Brazil.
Pendidikan bercerita – dengan guru sebagai pencerita – mengarahkan murid – murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Lebih buruk lagi, murid diubahnya menjadi “bejana – bejana”, wadah – wadah kosong untuk diisi oleh guru. Semakin penuh dia mengisi wadah – wadah itu, semakin baik pula seorang guru. Semakin patuh wadah – wadah itu untuk diisi semakin baik pula mereka sebagai murid.
Inilah konsep pendidikan “gaya bank”, dimana ruang gerak yang disediakan bagi kegiatan para murid hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan menyimpan. Mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi pengumpul dan pencatat barang – barang simpanan sehingga miskin daya cipta dan daya ubah seorang murid.
Dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa – apa. Menganggap bodoh secara mutlak pada orang lain, sebuah ciri dari ideology penindasan, berarti mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pencarian.
Kemampuan pendidikan gaya bank untuk mengurangi atau menghapuskan daya kreasi para murid, serta menumbuhkan sikap mudah percaya, menguntungkan kepentingan kaum penindas yang tidak berkepentingan dengan dunia yang terkuak atau yang berubah. Kaum penindas memanfaatkan “humanitarianisme” mereka untuk melindungi situasi menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Secara naluriah mereka akan selalu menentang setiap usaha percobaan dalam bidang pendidikan yang akan merangsang kemampuan kritis dan tidak puas dengan pandangan terhadap dunia yang berat sebelah, tetapi selalu mencari ikatan yang menghubungkan satu hal dengan hal – hal lainnya atau satu masalah dengan masalah lainnya. Sesungguhnya, kepentingan kaum penindas adalah “mengubah kesadaran kaum tertindas, bukan situasi yang menindas mereka”.
“Humanism” dari pendekatan gaya bank menutupi suatu usaha untuk menjadikan manusia sebagai benda terkendali (automaton) – suatu penolakan terhadap fitrah ontologis mereka untuk menjadi manusia seutuhnya.
Dalam konsep pendidikan gaya bank adalah anggapan akan adanya dikotomi antara manusia dengan dunia: manusia semata – mata ada di dalam dunia, bukan bersama dunia atau orang lain; manusia adalah penonton bukan pencipta. Dalam pandangan ini manusia bukanlah makhluk yang berkesadaran (corpo consciente); dia lebih merupakan pemilik sebuah kesadaran; suatu “jiwa” kosong yang secara pasif terbuka untuk menerima apa saja yang disodorkan oleh realitas dunia luar.
Peranan pendidik adalah mengatur cara dunia “masuk ke dalam” diri para murid. Tugasnya adalah mengatur suatu proses yang berlangsung secara spontan, “mengisi” para murid dengan menabungkan informasi yang dia anggap sebagai pengetahuan yang sebenarnya. Karena manusia “menerima” dunia secara pasif, maka pendidikan akan membuat mereka lebih pasif lagi, menjadikan mereka agar sesuai dengan dunia. Manusia yang terdidik adalah manusia yang telah disesuaikan, karena dia lebih “cocok” bagi dunia. Diterjemahkan kedalam praktik, konsep ini sesuai sekali dengan tujuan – tujuan para penindas yang ketentramannya tergantung pada seberapa cocok manusia bagi dunia yang telah mereka ciptakan, dan seberapa kecil mereka mempersalahkan hal ini.
Semakin lengkap kesesuaian mayoritas manusia dengan tujuan – tujuan yang telah ditentukan oleh minoritas manusia untuk mereka (dengan demikian merampas hak mereka untuk memiliki tujuan sendiri), semakin mudah pihak minoritas melangsungkan kekuasaan. Teori dan praktik pendidikan gaya bank mengabdi kepada tujuan – tujuan tersebut dengan cara yang sungguh efisien. Pelajaran – pelajaran yang verbalistik, bahan bacaan yang telah ditentukan, metode – metode untuk menilai “ilmu pengetahuan”, jarak antara guru dan murid, ukuran – ukuran bagi kenaikan kelas: segala sesuatu dalam pendekatan siap-pakai ini melumpuhkan pikiran.
Hanya melalui komunikasi manusia dapat menemukan hidup yang bermakna. Berpikir murni, yakni berpikir atas dasar keterlibatan dengan realitas, tidak dilakukan jauh di puncak menara gading, tetapi hanya dalam komunikasi.
Oleh karena pendidikan gaya bank bertolak dari suatu pengertian yang keliru tentang manusia sebagai obyek, maka dia tidak akan mampu mengembangkan apa yang disebut oleh Fromm dalam The Heart of Man sebagai biofili, tetapi justru sebaliknya mengembangkan nekrofil.
Konsep pendidikan gaya bank, yang mengabdi pada kepentingan – kepentingan penindasan, adalah juga nekrofilis. Berdasar pada pandangan tentang kesadaran yang mekanistis, statis, naturalistis dan terkotak, dia menjadikan murid sebagai obyek – obyek yang harus menerima. Dia selalu berusaha mengendalikan pikiran dan tindakan, mengarahkan manusia agar menyesuaikan diri terhadap dunia dan menghalangi kemampuan kreatif mereka.
Ketika usaha – usaha untuk berbuat secara bertanggung jawab dikecewakan, ketika mereka mendapatkan diri tidak dapat memanfaatkan kemampuan – kemampuan mereka, maka ketika itulah manusia menderita.
Pembebasan adalah sebuah praksis: tindakan dan refleksi manusia atas dunia untuk dapat mengubahnya. Manusia saling mengajar satu sama lain, ditengahi oleh dunia, oleh obyek – obyek yang dapat diamati yang dalam pendidikan gaya bank “dimiliki” oleh guru semata.
Konsep pendidikan gaya bank (yang cenderung membuat dikotomi terhadap apa saja) membedakan dua tahap kegiatan seorang pendidik. Pertama, pendidik mengamati sebuah obyek yang dapat diamati selama dia mempersiapkan bahan pelajaran di kamar atau laboratoriumnya; dan yang kedua dia menceritakan kepada murid tentang obyek tersebut. Para murid tidak diminta untuk mengerti, tetapi menghapal apa yang diceritakan oleh guru. Murid juga tidak berpraktik melakukan pengamatan, oleh karena obyek yang menjadi sasaran pemahaman adalah milik guru, dan bukan medium yang mengundang refleksi kritis dari guru maupun murid.
Metode pendidikan hadap – masalah tidak membuat dikotomi kegiatan guru – murid ini; guru selalu “menyerap”, baik ketika dia mempersiapkan bahan pelajaran maupun ketika dia berdialog dengan para murid. Peran seorang pendidik hadap – masalah adalah menciptakan, bersama dengan murid suatu suasana di mana pengetahuan pada tahap mantera (doxa) diganti dengan pengetahuan sejati pada tahap ilmu (logos).
Pada salah satu acara pertemuan kelompok binaan program kami di Cile, kelompok itu mendiskusikan (dengan menggunakan metode kodifikasi) konsep kebudayaan secara antropologis. Di tengah – tengah diskusi, seorang petani yang menuntut standar gaya bank menyatakan : “sekarang saya paham bahwa tanpa manusia maka dunia pun tidak ada.” Pemandu belajarnya kemudian menanggapi “Seandainya, sebagai perumpamaan saja, semua manusia di dunia tiba – tiba mati, tetapi bumi masih tetap ada, di samping pohon – pohon, burung – burung, binatang, sungai – sungai, lautan, bintang – gemintang . . . , bukankah semua itu merupakan sebuah dunia?” “Oh bukan,” jawab si petani dengan sungguh – sungguh. “sebab tidak ada seorangpun yang akan mengatakan : “Ini sebuah dunia”.
Petani tersebut bermaksud menyatakan pikirannya bahwa tidak akan ada kesadaran tentang dunia jika dunia kesadaran itu sendiri tidak ada. “Aku” tidak akan ada jika tidak ada “bukan-aku”. Sebaliknya, “bukan aku” tergantung kepada keberadaanku. Dunia yang menimbulkan kesadaran menjadi dunia dari kesadaran tersebut. Demikianlah dinyatakan Satre seperti telah dikutip di atas. “kesadaran dan dunia tampil secara serempak”.
Dalam pendidikan hadap – masalah, manusia mengembangkan kemampuannya untuk memahami secara kritis cara mereka mengada dalam dunia dengan mana dan dalam mana mereka menemukan diri sendiri; mereka akan memandang dunia bukan sebagai realitas yang statis, tetapi sebagai realitas yang berada dalam proses, dalam gerak perubahan.
Di dalam kata kita menemukan dua dimensi, refleksi dan tindakan, dalam suatu interaksi yang sangat mendasar hingga bila salah satunya dikorbankan – meskipun hanya sebagaian – seketika itu yang lain dirugikan. Tidak ada kata sejati yang pada saat bersamaan juga tidak merupakan sebuah praksis. Dengan demikian, mengucapkan sebuah kata sejati adalah mengubah dunia.
Jika dalam mengucapkan kata – katanya sendiri manusia dapat mengubah dunia dengan jalan menamainya, maka dialog menegaskan dirinya sebagai sarana di mana seseorang memperoleh makna sebagai manusia. Dialog karena itu, merupakan kebutuhan ekstensian. Karena dalam dialog merupakan perjumpaan di antara orang – orang yang menamai dunia, maka tidak boleh menjadi suatu keadaan dimana sejumlah orang menamai dunia dengan mengatasnamakan orang lain.
Dialog tidak dapat berlangsung, bagaimanapun, tanpa adanya rasa cinta yang mendalam terhadap dunia dan terhadap sesame manusia. Di pihak lain, dialog tidak dapat terjadi tanpa kerendahan hati. Dialog selanjutnya menuntut adanya keyakinan yang mendalam terhadap diri manusia, keyakinan pada kemampuan manusia untuk membuat dan membuat kembali, untuk mencipta dan mencipta kembali, keyakinan pada fitrahnya untuk menjadi manusia seutuhnya (yang bukan hak istimewa sekelompok elite, tetapi hak kelahiran semua manusia. Keyakinan terhadap diri manusia adalah sebuah prasyarat a priori bagi dialog, “manusia dialogis” percaya pada orang lain bahkan sebelum dia bertatap muka dengannya.
Dialog juga tidak dapat terjadi tanpa adanya harapan. Harapan berakar pada ketidaksempurnaan manusia, dari mana mereka secara terus – menerus melakukan usaha pencarian – pencarian yang hanya dapat dilakukan dalam kebersamaan dengan orang lain.
Pendidikan yang dialogis, yakni guru-yang-murid dari model hadap – masalah, isi bahan pelajaran dalam pendidikan bukanlah sebuah hadiah atau pemaksaan – potongan – potongan informasi yang ditabungkan ke dalam diri para murid – tetapi berupa “penyajian kembali” kepada murid tentang hal – hal yang ingin mereka ketahui lebih banyak, secara tersusun, sistematik dan telah dikembangkan. Penelitian dari apa yang saya istilahkan “dunia tema” (thematic universe) rakyat – sebagai kompleks dari “tema – tema generative” (generative themes) – mengesahkan dialog pendidikan sebagai praktik kebebasan.
Tindakan yang dilakukan binatang adalah sekedar eksistensi dari dirinya sendiri, maka hasil tindakan tersebut adalah juga tak terpisahkan dari diri mereka sendiri; binatang tidak mampu memberi tujuan bagi tindakannya atau memberi makna terhadap perubahan dunia yang dilakukan di luar dunianya sendiri. Binatang pada dasarnya merupakan “makhluk dalam dirinya sendiri.
Binatang adalah makhluk yang tidak menyejarah. Bagi binatang, dunia ini tidak memiliki sesuatu yang “bukan-aku” yang menjadikan dirinya sebagai suatu “aku”. Binatang tidak ditantang oleh konfigurasi yang mereka hadapi; mereka semata – mata hanya dirangsang. Kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang menantang resiko, karena mereka tidak sadar yang diketahui melalui refleksi, tetapi begitu saja “tertangkap” melalui isyarat yang menandainya; karena itu dia tidak membutuhkan tanggapan melalui pertimbangan pikiran.
Sebaliknya, manusia memiliki kesadaran akan tindakan dan dunia dimana mereka berada. Mereka bertindak sesuai dengan arah yang ditujunya, menetapkan keputusan – keputusan bagi dirinya sendiri dan bagi kaitannya dengan dunia serta sesame manusia lainnya, dan mencampuri dunia dengan kehadirannya yang kreatif dengan cara memperbaharui dunia.
Manusia, sebaliknya, karena memiliki kesadaran akan diri sendiri dan kesadaran akan dunia – karena mereka memang makhluk berkesadaran – mengada dalam suatu hubungan dialektis antara ketentuan – ketentuan yang membatasinya dengan kemerdekaan yang dimilikinya.
Penelitian tema yang berlangsung dalam dunia manusia tidak dapat direduksi menjadi kegiatan mekanis. Sebagai proses pencarian, pengetahuan, dan dengan demikian kreasi, dia menuntut para peneliti untuk menemukan saling – keterkaitan antarmasalah, dalam rangka tema – tema bermakna. Penelitian akan menjadi sangat mendidik jika dia sangat kritis, dan sangat kritis jika dia menghindari patokan – patokan sempit dari pandangan terhadap realitas yang berat sebelah atau “terkotak”, serta tetap menerapkan pemahaman terhadap realitas secara keseluruhan. Dengan demikian proses pencarian bagi tema – tema bermakna harus mencakup masalah perkaitan antartema, masalah pengungkapan tema – tema itu sebagai permasalahan, dan masalah konteks sejarah dan kebudayaannya.
Hal yang penting, dari sudut pandang pendidikan yang membebaskan, adalah agar manusia merasa sebagai tuan bagi pemikirannya sendiri dengan berdiskusi mengenai pemikiran dan pandangan tentang dunia yang secara jelas atau tersamar terungkap di dalam tanggapan – tanggapan mereka sendiri dan kawan – kawannya. Oleh karena pandangan terhadap pendidikan ini bertolak dari keyakinan bahwa dia tidak dapat menyajikan programnya sendiri, tetapi harus menyusun program ini secara dialogis dengan masyarakat, maka dia berperanan untuk memperkenalkan pendidikan bagi kaum tertindas, yang dalam perkembangnnya kaum tertindas harus mengambil bagian.
Aktivitas manusia yang berupa tindakan dan refleksi; inilah praksis; inilah perubahan dunia. Sebagai praksis dia memerlukan teori untuk menerangi. Aktivitas manusia adalah teori dan praktik; itulah refleksi dan tindakan. Pernyataan Lenin yang terkenal: “Tanpa teori revolusi tidak akan ada gerakan revolusi”, berarti bahwa suatu revolusi akan terlaksana tanpa verbalisme atau aktivisme, tetapi dengan praksis, yakni dengan refleksi dan tindakan yang diarahkan pada struktur – struktur yang hendak diubah.
Praksis revolusi tidak dapat menoleransi dikotomi absurd dimana praksis rakyat hanya sekedar pelaksanaan keputusan – keputusan para pemimpin – suatu dikotomi yang mencerminkan metode resep dari elite penguasa. Praksis revolusi merupakan sebuah kesatuan, dan para pemimpin tidak dapat memperlakukan kaum tertindas sebagai milik mereka.
Revolusi tidak dilaksanakan baik oleh para pemimpinnya untuk rakyat, tidak juga oleh rakyat untuk para pemimpin, melainkan oleh keduanya yang bertindak bersama – sama dalam solidaritas yang tidak tergoyahkan. Solidaritas ini lahir hanya bila para pemimpin menyaksikannya melalui perjumpaan mereka yang rendah hati, penuh kasih serta berani, dengan rakyat. Dialog, sebagai perjumpaan antarmanusia untuk “menamai” dunia, merupakan prasyarat dasar bagi humanisasi sejati mereka. Sebagaimana dikatakan Lenin, semakin suatu revolusi membutuhkan teori, semakin para pemimpinnya harus bersama rakyat agar dapat berhadapan melawan kekuasaan penindas.
Seperti yang disebutkan Lenin sebelumnya bahwa teori itu sangat penting untuk mengetahui sebuah tindakan apakah termasuk anti diaologi yang menuju penindasan atau dialogis yang menuju kebebesan. Teori – teori tindakan yang antidialogis antara lain penaklukan, pecah dan kuasai, dan manipulasi.
(Penaklukan) watak pertama dari tindakan antidialogis adalah keharusan adanya penaklukan. Penaklukan memaksakan kehendak kepada mereka yang ditaklukkan, dan menjadikan mereka miliknya.
Merupakan keharusan bagi kaum penindas untuk mendekati rakyat agar dapat membuat mereka tetap pasif melalui penaklukan. Pendekatan ini, tentu saja, tidak berunsur ada bersama rakyat, maupun menuntut adanya komunikasi sejati. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkan mitos – mitos kaum penindas yang tidak terelakkan bagi keberlangsungan status quo contohnya, mitos bahwa tatanan menindas adalah suatu “masyarakat bebas”; mitos bahwa semua orang bebas untuk bekerja di mana mereka kehendaki, dan bila mereka tidak senang dengan majikannya mereka dapat meninggalkan dan mencari pekerjaan yang lain; mitos bahwa tatanan ini menghormati hak – hak manusia dan karena itu patut dihargai; mitos bahwa siapapun yang rajin bekerja dapat menjadi pengusaha – lebih buruk lagi, mitos bahwa pedagang kaki lima adalah sama dengan pemilik pabrik besar sebagai pengusaha; mitos mengenai hak pendidikan universal, ketika dari seluruh anak – anak Brazil yang memasuki sekolah dasar hanya sebagian kecil saja yang mencapai perguruan tinggi; mitos mengenai persamaan derajat manusia, ketika pertanyaan: “Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara?” masih berlaku di antara kita; mitos tentang kepahlawanan kelas penindas sebagai pembela “peradaban Kristen Barat” menentang “barbarisme kaum materialis”; mitos karitas dan kedermawanan kaum elite untuk menyatakan bahwa apa yang sesungguhnya mereka lakukan sebagai suatu kelas adalah untuk memelihara “perbuatan – perbuatan terpuji (kemudian diperhalus menjadi mitos tentang “bantuan tanpa pamrih” yang pada tingkat internasional dikritik tajam oleh Paus Johanes XII). Lebih dari itu, Negara – Negara dengan ekonomi yang lebih maju harus berhati –hati jangan sampai, dalam memberi bantuan kepada Negara – Negara miskin, mereka mencoba memengaruhi situasi politik yang berlaku untuk kepentingan sendiri, serta berusaha untuk menguasai mereka. Seandainya terdapat usaha – usaha semacam itu, maka dia tidak pelak lagi merupakan bentuk lain dari kolonialisme yang, sekalipun berkedok nama lain, sebenarnya mencerminkan penjajahan lama mereka yang sudah ketinggalan zaman, yang sekarang telah ditinggalkan oleh banyak Negara. Bila hubungan internasional dihambat seperti ini, maka pembangunan semua bangsa secara tertib akan terancam. Dari surat Ensiklik Mater et Magistra.; mitos bahwa elite penguasa, dengan “menyadari kewajiban – kewajiban mereka”, mengusahakan kemajuan bagi rakyat, sehingga rakyat, dalam ungkapan rasa terima kasih, hendaknya menerima kata – kata kaum elite serta menyesuaikan diri terhadap mereka; mitos bahwa pemberontakan adalah suatu dosa terhadap Tuhan; mitos mengenai kekayaan pribadi sebagai sangat penting bagi perkembangan pribadi manusia (sepanjang kaum penindas merupakan satu – satunya kelas manusia sejati); mitos tentang ketidakjujuran kaum tertindas, di samping mitos tentang inferioritas alamiah kaum tertindas dan superioritas kaum penindas. Memmi menunjuk pada citra yang dibangun kaum penjajah dalam diri kaum terjajah; “Dengan tuduhannya kaum penjajah menjadikan kaum terjajah sebagai orang – orang malas. Dia menilai kemalasan itu merupakan pembawaan dalam diri kaum tertindas.
Semua mitos tersebut (dan lain – lain yang dapat pembaca tambahkan), yang internalisasinya sangat penting bagi usaha menundukkan kaum tertindas, disajikan kepada mereka melalui propaganda dan slogan – slogan yang terorganisasi dengan baik, melalui media “komunikasi” massa – dianggapnya keterasingan semacam itu sungguh – sungguh merupakan komunikasi.
(Pecah dan Kuasai) Setelah minoritas penindasan menaklukkan dan menguasai mayoritas rakyat, mereka harus memecah – belah dan menjaganya agar tetap terpecah, supaya dapat terus berkuasa. Kaum penindas mematahkan dengan segala cara (termasuk kekerasan) setiap aksi yang sekalipun masih pada tahap dini dapat membangkitkan rasa butuh persatuan di kalangan rakyat. Konsep – konsep seperti halnya kesatuan, organisasi, dan perjuangan, seketika dicap berbahaya. Sesungguhnyalah, tentu saja, konsep – konsep ini memang berbahaya – bagi kaum penindas – oleh karena realisasi dari semua itu merupakan keniscayaan bagi aksi – aksi pembebasan.
Kaum penindas tidak mau memajukan masyarakat secara keseluruhan, tetapi hanya para pemuka yang terpilih. Pilihan kedua ini, dengan memelihara keterasingan, menghambat munculnya kesadaran serta keterlibatan kritis dalam suatu realitas total. Tanpa adanya keterlibatan kritis, akan senantiasa sulit untuk mempersatukan kaum tertindas sebagai suatu kelas.
(Manipulasi) semakin rendah kesadaran politik rakyat (di desa atau kota) semakin mudah mereka dimanipulasi oleh mereka yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Salah satu metode manipulasi adalah menanamkan cita rasa borjuis kepada orang – orang untuk mencapai sukses pribadi.
Marilah kita sekarang menganalisis teori tindakan budaya dialogis dan mencoba melihat unsur – unsur pembentuknya.
(Kerja Sama) dalam teori tindakan dialogis, para pelaku berkumpul dalam kerja sama untuk mengubah dunia. Dialog, sebagai komunikasi esensial, harus mendasari setiap kerja sama.
(Persatuan untuk Pembebasan) dalam teori tindakan dialogis para pemimpin harus menyerahkan dirinya bagi usaha tanpa kenal lelah bagi persatuan kaum tertindas – dan persatuan para pemimpin dengan kaum tertindas – untuk mencapai pembebasan.
(Organisasi) organisasi bukan hanya berkaitan langsung dengan persatuan, namun juga merupakan perkembangan yang wajar dari persatuan itu. Oleh karena itu, usaha para pemimpin dalam hal persatuan adalah niscaya juga suatu usaha untuk mengorganisasi rakyat, yang menuntut kesaksian bagi kenyataan bahwa perjuangan bagi pembebasan adalah tugas bersama.
Unsur – unsur esensial dari kesaksian yang tidak berbeda sepanjang sejarah, mencakup : konsistensi antara kata dan tindakan; tekad yang mendorong kesaksian untuk menghadapi kehidupan sebagai resiko yang ajek; radikalisasi (bukan sektarianisme) yang membimbing baik kesaksian maupun orang yang menerima kesaksian itu untuk bertindak lebih banyak; keberanian untuk mencintai (yang sama sekali bukan memberi akomodasi bagi dunia yang tidak adil, melainkan mengubah dunia tersebut atas nama pembebasan manusia yang semakin longgar); serta keyakinan terhadap rakyat, karena untuk merekalah kesaksian dibuat – sekalipun kesaksian untuk rakyat, karena hubungan dialektis mereka dengan elite penguasa juga memengaruhi pihak terakhir itu (yang menanggapi kesaksian itu menurut kebiasaan mereka)
(Sintesa Kebudayaan) Sintesa kebudayaan merupakan suatu cara bertindak untuk menghadapi kebudayaan itu sendiri, sebagai penjaga dari struktur – struktur yang membentuk dirinya. Aksi kebudayaan, sebagai aksi sejarah, adalah sarana untuk menggeser kebudayaan kaum pengusaha yang terasing serta mengasingkan. Dalam arti inilah, setiap revolusi sejati merupakan revolusi kebudayaan.
Tuntutan upah saja tidak dapat membawa penyelesaian tuntas. Hakikat penyelesaian ini dapat ditemukan dalam pernyataan yang dikutip di atas dari para uskup Dunia Ketiga bahwa “bila kaum buruh tidak dapat menjadi pemilik dari karya mereka sendiri, maka semua perubahan structural tidak akan efektif . . . mereka (harus) menjadi pemilik, bukan penjual, dari karya mereka sendiri . . . (sebab) setiap pembelian atau penjualan karya manusia merupakan satu jenis perbudakan”.
Untuk mencapai kesadaran kritis mengenai kenyataan bahwa sangat penting artinya untuk menjadi “pemilik dari karya sendiri”, bahwa karya “merupakan bagian dari pribadi manusia,” dan bahwa “seorang manusia tidak dapat dijual ataupun menjual dirinya sendiri,” berarti harus maju selangkah keluar dari khayalan penyelesaian semu. Melakukan perubahan sejati atas realitas, dengan memanusiakan realitas itu, akan berarti memanusiakan manusia.
Dalam teori tindakan antidialogis, serangan kebudayaan melalui tujuan – tujuan manipulasi, yang pada gilirannya melayani tujuan – tujuan penaklukan, dan penaklukan melayani tujuan – tujuan dominasi. Sintesa kebudayaan melayani tujuan – tujuan organisasi; organisasi melayani tujuan – tujuan pembebasan.
Dalam resensi singkat diatas, kita melihat bagaimana analisa dari Paulo Freire tentang sebuah system penaklukan, penindasan dan perbudakan yang dijaga terus oleh kaum penindas. Salah satu alat mereka yaitu mencemari system pendidikan dengan mitos-mitos busuk yang berusaha menjauhkan manusia dari hakikatnya sebagai manusia sejati. Dalam analisa Paulo Freire kita bisa menemukan beberapa kesulitan terutama saya (sebagai pembaca dan pembuat resensi) yaitu kesulitan untuk memahami karyanya secara kompleks. Hal ini mungkin dikarenakan buku yang saya baca adalah buku terjemahan yang kemungkinan besar tidak bisa menyampaikan makna setiap kalimat yang dituliskan Paulo Freire dan buku merupakan buku filsafat yang berusaha membongkar fikiran kita dan menginjeksikan sesuatu berdasarkan hakikatnya. Tetapi secara keseluruhan buku ini sangat disarankan untuk dibaca. Karena diakui resensi ini tidaklah dapat mewakili buku terjemahan Paulo Freire (Pendidikan Kaum Tertindas) apalagi buku asli dari Freire.